Suatu hari, di sepotong pagi, di balik jajaran kursi dan kubikel sepi. Kutemukan senyummu di antara cangkir kopi. Kala itu, engkau hanya diam tanpa pejam. Seolah hendak mengucap “Selamat datang”. Kutuangkan untukmu senyuman manis. Kursi dan meja beradu tajam. “Hei! sudah lama kita bersua, namun tak sepatah kata pun saling sapa.” Tak apa. Kita bukan siapa-siapa. Aku hanya terpesona, dalam keheningan kita dan kata.
Sekian candra berlalu, berganti bulan sabit baru.
Di balik senyummu, aku menemukan diriku, jatuh ke dalam keindahan sinar matamu. Tajam menghujam. Tapi kau selalu saja diam. Masih bertahan dalam senyap. Tak sebongkah kalimat pun terucap. Meski hanya seringai basa-basi tanpa arti. Tanpa kusadari, jiwaku kian berlari, menujumu.
Dalam dadaku, tersimpan sepi. Tertutup rapi. Saat kau menghilang, tak satu pun kabar yang menepi. “Ah, ini bukan rindu, hanya perasaan basi.” sangkalku. Ribuan kata terjebak, ingin kudengungkan dalam telingamu. Kuserahkan kata “Hei, aku di sini, menunggumu dalam biru-biru haru.”
Kau dan aku, Phobos dan Deimos, aku berotasi mengelilingi rindu, sekering Mars. Menantikan hangat dekap, dalam sunyi senyap. Wahai kamu, ada yang menyapamu diam-diam, ada yang mencintaimu dalam diam, ada yang mecintaimu dalam-dalam, ada yang diam-diam mencintaimu. Mengertilah!
Candra berlalu, roda kereta melaju, menuju Stasiun Tugu. Kini engkau tak lagi bersamaku.
Candi-candi senja, izinkan aku berkelana, ke dalam jiwanya. Sukmaku-sukmanya, menjelma, manunggaling kawula-raga, kawula-rindu. Berwisata di pedalaman Jawa.
Aku ragu saat ingin bertemu. Ingin kukurung dan kularung rasa pilu saat tak berjumpa denganmu. Di antara stupa Borobudur, mimpiku melayang, bertebaran, berserakan, di atas bongkahan arca-arca Buddha tanpa kepala. Tanpa asa.
Tak ada yang menduga, kisah kita-tercipta dari plataran Kamadatu. Dari olah rasa, menapaki trap-trap candi bertingkat. Bertahap-tahap, penuh harap. Berjajar stupa-stupa Buddha, menyungkup begitu rupa.
Mengertilah! Padamu ingin kusampaikan. Di balik candi ini, kisah kita abadi.
Di ufuk barat, semburat candikala berwarna jingga. Pertanda bagi orang Jawa, menghentikan roda karya-cipta. Bagaskara hendak bersemayam, menuju nirwana.
Wahai kamu, kutemukan jiwamu, berpagut maut. Terjebak di kepingan relief candi, memandangku pangling, saat kangen berkeliling. Cakra manggilingan berputar mengucap mantra, searah pradaksina. Di puncak arupadatu rinduku duduk bertapa, berputar ke arah prasawiya. Semoga Gusti ‘kan berkenan merestui.
Candra berlalu, musim berganti. Kini kau makin hilang. Namun asaku terus berpijar dan tak kunjung pudar, seperti cahaya badar.
Aku terus berkelana, menujumu. Meski tak lagi mudah, untuk bersatu. Bahkan, sekadar menyapamu. Kau, ketahuilah, aku ingin memanjangkan waktu. Untuk terus bersamamu.
Roda waktu terus berputar. Kangenku tak jua pudar. Di langit, ratri kian tinggi. Larut dalam bulan mati. Angsa-angsa senja berkeliaran di pinggiran telaga. Andaikan aku menjelma bulan, ‘kan kusinari kau sepanjang malam.
Tentang kita, hanyalah sepasang jika. Kekal dirawat jarak, dekat yang tak pernah bisa diikat. Lekat yang tak bisa didekap.
Malam ini, hujan deras sekali, rindu menggigil berteduh di bawah payung, lupa membawa pelukmu yang hangat. Ingatlah! Sebelum hujan memilih nama, jarak kita tidak terlalu jauh, hanya setetes air mata.
Asaku terus berkelana.
Hingga ke altar Prambanan ku mencari, sang mudra hyang manca. Bilakah kita bersua, dalam puja dan samadi doa. Segala tentangmu, kubingkai agar tak menjadi bangkai. Kuruwat, kurawat agar tak satu pun terlewat. Di antara gugus pilu dan nyalang harapan, rindu hanyalah serpihan tengkorak, terserak dibentangkan jarak, hanya bisa diukur dengan sajak
Candra terus berlalu. Mengantarku pada tumpukan asa.
Aku hendak ke seberang bengawan, menjemputmu dengan jung bersauh dayung. Di jagat raya ini, kisah kita tak sempurna. Wahai aku, ingatlah! Selalu lafalkan zikir, agar kisah kasih tak mubazir. Seandainya mimpi terbakar, tetaplah bangkit penuh kelakar.
Kini aku terdampar. Di halaman pendopo kisahku bercerita, diiringi para penayub sudah menunggu. Dengan alunan gending dandangula yang bertalu-talu.
Purnama siddhi kian tinggi. Di sepertiga pagi. Aku mengerti, harus siap menghadapi turbulensi.
Di atas sajadah, perkenankan aku menyembah dan berserah. Bersimpuh, mengaduh, pasrah ke hadirat-Nya. Larut dalam tembang pangkur. Menyingkur dari hiruknya buana yang kelak lebur.
~ Ratu Boko – Yogyakarta dan segala tentang kita, yang tak berkesudahan.
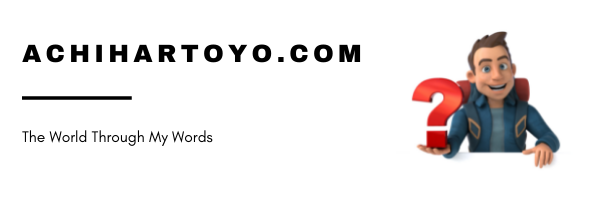








6 comments
keren bangeett… kisah rindu tak berkesudahan yang digambarkan dengan apik dan klasik., suerr kereeen..kata2nya duh dapat dari mana sih ituu…
kutahu cintamu itu tertuju padanya, kenapa tak kau katakan saja?
hahahaha
hahaha
Kok aku bacanya meresapi banget yaa.
Apalagi kalau liat candinya. Rindumu sebegitu kokoknya seperti candi itu kah?
kyk candi gak bs goyah hahaha
Duhh jadi halu,,,,
halu-halu bandung