“Penumpang yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Tawang Jaya, yang akan mengantar kita ke tujuan akhir Stasiun Tawang. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 4 jam 58 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas, pada perjalanan kali ini. Terima kasih.”
-

Beragam koleksi batik cantik nusantara
Suara khas “mbak-mbak” dari pengeras suara, mengantar saya dan rombongan duduk manis di bangku kereta yang menuju Kota Pekalongan. Beberapa penumpang masih tampak mengatur barang bawaan di atas kompartemen. Sebagian petugas kereta api, sibuk membantu penumpang mencari bangkunya masing-masing.
Suasana seperti ini selalu berhasil membuat saya terharu. Hawa “mudik” ke Jawa sangat kental terasa, meski perjalanan kali ini bukan untuk mudik ke kampung halaman, melainkan ke Kota Batik Pekalongan. Ya, kali ini saya bersama teman-teman, ingin menjelajahi beberapa wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Mulai dari Pekalongan, Tegal, Slawi, hingga Brebes. Salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Jawa Tengah.
Suhu di dalam kereta api hanya berkisar dua puluh lima derajat. Tidak terlalu dingin. Jaket yang menempel di badan pun saya lepas. Perjalanan kereta malam menuju Pekalongan akan ditempuh sekitar lima jam-an. Beberapa itinerary sudah dibuat untuk memudahkan penjelajahan kita esok hari. Sesuai rencana, kami akan mengawali perjalanan dari Kota Pekalongan. Tak sabar rasanya menunggu pagi dan menikmati sarapan khas nasi megono. Rasa lelah setelah berjuang melawan macet Kota Jakarta, sukses membuai kita menuju alam mimpi. Penutup mata dan bantal leher sudah menempel dengan sempurna.
“Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi, Kereta Api Tawang akan tiba di Stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk, sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda, menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.“
Kembali suara khas ‘mbak-mbak’ dari pengeras suara membangunkan tidur kami. Usai menunaikan ibadah salat Subuh, kami segera berkemas dan bersiap untuk turun di Stasiun Pekalongan. Jam di layar ponsel menunjukkan waktu pukul 5 lewat 20 menit saat kaki saya menapaki Stasiun Pekalongan. Matahari pagi di Kota Pekalongan cukup cerah. Deretan becak berjajar di depan stasiun menyambut para penumpang. Meski tidak terlalu besar, Stasiun Pekalongan cukup sibuk melayani penumpang. Beberapa fasilitas dan peron tampak sedang direnovasi untuk kenyamanan penumpang.
Tahun 1899, Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, N.V. (SCS) telah membangun dan meresmikan jalur sepur di Pulau Jawa. Awalnya, pembangunan ini digunakan sebagai jalur alternatif untuk mengangkut gula selain dari Jalan Raya Pos-nya Daendels di pesisir utara Pulau Jawa. Termasuk Stasiun Pekalongan yang menjadi bagian dari proyek pembangunan jalur sepur tersebut. Sejak pertama kali dibuka hingga sekarang, Stasiun Pekalongan telah dilintasi jutaan manusia dari beragam latar dan jabatan.

Di pintu keluar stasiun yang berseberangan langsung dengan sebuah hotel ternama, taksi daring yang kami pesan sudah menunggu. Dengan sigap, driver taksi daring memasukkan koper-koper ke dalam bagasi saat kami tiba. Pagi itu, kami berencana menuju hotel untuk menjemput teman yang sudah lebih dulu datang, sekaligus membersihkan diri. Di sepanjang perjalanan, di beberapa ruas trotoar menuju hotel, tampak deretan penjaja makanan untuk sarapan, sibuk menggelar dagangan. Suasana khas seperti ini benar-benar saya rindukan saat berada di pedalaman Jawa. Termasuk Pekalongan.
Jika dirunut dari sejarahnya, nama Pekalongan sendiri berasal dari istilah “topo ngalong”nya Joko Bau (Bau Rekso) putra Kyai Cempaluk yang dikenal sebagai pahlawan daerah Pekalongan. Joko Bau yang di kemudian hari berganti nama menjadi Bau Rekso, diperintah Sultan Agung untuk menyiapkan pasukan dan membuat perahu membentuk armada untuk melaksanakan serangan terhadap kompeni di Batavia (1628 dan 1629). Saat mengalami kegagalan, Bau Rekso memutuskan untuk melakukan tapa seperti kalong atau kelelawar (menggantung) di sebuah hutan bernama Gambiran. Dari asal ‘topo ngalong’ inilah kemudian muncul nama Pekalongan.
Kesibukan pagi itu dimulai dari perburuan menu untuk sarapan. Saya sendiri sudah ‘ngidam’ nasi megono sejak berangkat dari Jakarta. Usai membersihkan diri dan meluruskan punggung sejenak, perburuan sarapan pun dimulai. Tidak jauh dari hotel, sebuah rumah makan berkonsep ‘masakan rumahan’ menyita perhatian kita. Tak butuh waktu lama, kami segera masuk dan memilih beragam masakan yang disajikan. Menu garang asem berkuah gelap dengan taburan cabe rawit tampak menggoda. Impian saya untuk menyicipi megono pun teralihkan. Selain garang asem, beragam menu lainnya juga tampak menggoyahkan iman.
Lupakan diet saat liburan di Kota Pekalongan. Kuliner di kota ini tidak pernah mengecewakan saya. Beruntungnya saya memiliki teman-teman yang hobi berburu kuliner daerah dan suka jajan di pinggir jalan.
Menelisik Ragam Batik Nusantara di Museum Batik Pekalongan
Berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, nama Pekalongan tak bisa lepas dari jalur Pantura. Popularitas Pantura sendiri dimulai saat Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Dalam bukunya “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels”, Pram (PAT) menyebutkan bahwa pembangunan Jalur Pantura yang membentang dari Anyer hingga Panarukan ini, sebagai ‘genosida’ oleh kolonial Belanda.

Tak terhitung jumlah korban tewas yang berasal dari pekerja saat membuat Jalan Raya Pos ini. Baik karena kelelahan, kelaparan, maupun wabah malaria. Sebagai kota yang dilintasi Jalan Raya Pos (Pantura), Pekalongan memiliki penanda yang dibuat oleh Deandels: Mylpaal (titik nol) yang berada tepat di Lapangan Jatayu. Tak begitu jauh dari Museum Batik.
Saat saya melangkahkan kaki memasuki Museum Batik, tampak bangunan gedung loji berwarna putih, berdiri kokoh di depan Lapangan Jatayu. Gedung Museum Batik ini dibangun sejak 1906. Awalnya, gedung museum ini merupakan bekas kantor balai kota Pekalongan. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini pernah menjadi kantor keuangan yang membawahi tujuh pabrik gula di karesidenan Pekalongan.
Museum Batik ini memiliki tiga ruang pamer yang menampilkan ratusan koleksi kain batik Nusantara. Hawa panas khas pesisir langsung berubah sejuk saat kaki saya masuk ke dalam museum. Di bagian belakang gedung digunakan sebagai area lokakarya (workshop) bagi pengunjung yang ingin belajar membuat batik. Saya pun tak mau ketinggalan. Di ruang ini saya dan rombongan diajarkan bagaimana membuat selembar kain mori berwarna putih menjadi sebuah karya indah. Tak mudah memang.
Bahkan, membuat batik dengan menggunakan cap-dengan pola batik yang sudah diukir dalam lempengan logam atau kayu tidak bisa dibilang mudah. Apalagi membuat batik tulis yang dilukis manual, benar-benar membutuhkan jam terbang yang tinggi.
Tak heran bila selembar kain batik harganya bisa bernilai jutaan. Untuk membuatnya dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, hingga ketelitian. Mulai dari membuat pola dasar, menorehkan malam dengan menggunakan canting (nyanting), hingga proses mewarnai dan melorot malam. Semua membutuhkan ketekunan dari sang pengrajin. Dari mengikuti workshop ini, kami semakin menghargai sebuah karya dalam selembar kain batik.
Museum Batik ini buka setiap hari (termasuk hari Minggu dan libur besar). Tiket masuknya pun terbilang murah. Hanya lima ribu rupiah untuk pengunjung dewasa dan seribu rupiah untuk anak-anak. Dengan harga semurah ini, sudah fasilitasnya pun tidak mengecewakan. Tersedia internet gratis dan penitipan barang.
Menyicipi Soft Drink Jadoel “Limun Oriental” Khas Pekalongan
-

Ragam botol limun dengan varian rasa yang sensasional
Usai mengikuti kelas membatik, kami melanjutkan penjelajahan di Kota Pekalongan dengan berburu kuliner untuk mengisi perut siang itu. Lokasinya berada tepat di belakang Museum Batik. Hanya berjarak sekitar tujuh rumah. Nama kafenya Limun Oriental Cap Nyonya Shiluet, berdiri sejak 1920. Dari nuansa dan konsep kafe yang dihadirkan, kita serasa diajak kembali ke masa lalu. Jajaran kursi sedan jadul dan deretan pajangan kuno menarik perhatian saya.
Selain menikmati limun, di sini kita juga mengunjungi pabrik pembuatan minuman ‘Banyu Londo’ ini. Lokasinya berada di belakang kafe. Bangunan tua khas zaman kolonial Belanda masih dipertahankan seperti aslinya.
Pada zaman dahulu, saking mewahnya, minuman limun ini hanya bisa dinikmati oleh kaum priyayi Jawa di Kota Pekalongan. Limun Oriental memiliki tujuh varian rasa: Jeruk, Framboze, Nanas, Sirsak, Melon, Kopi Moka, dan Air Soda. Soft drink jadul ini memberikan sensasi rasa ‘semriwing’ saat menyesapnya karena terbuat dari racikan gula, sari buah, asam sitrat, air, dan karbondioksida. Hawa panas kota pesisir semakin menambah nikmatnya minuman ini.
Tidak cuma minuman limun yang bisa kita nikmati. Soto Tauto khas Pekalongan juga dihidangkan untuk mengisi perut saya dan rombongan. Selain itu, ayam geprek kekinian juga tersedia di kafe ini. Harganya pun tak membuat kantung jebol. Perut kenyang, hati pun riang.
Pasar Sentono, Sentra Batik dengan Harga Terbaik
Matahari sore sudah bertengger di ufuk barat. Penjelajahan di Kota Pekalongan belum usai. Destinasi terakhir sebelum pindah ke kota lain adalah Pasar Setono. Di sini kita bisa menemukan baju-baju dan kain batik berkualitas dengan harga terbaik. Pasar Setono ini semacam “Beringharjo atau ThamCit”nya Pekalongan.
Dari ujung ke ujung, mata kita disuguhi dengan jajaran kain batik beraneka corak. Tak perlu takut menawar, karena harga-harga baju batik di sini tergolong terjangkau untuk semua kalangan. Penjualnya pun ramah-ramah. Beberapa lembar baju batik sudah masuk ke dalam tas dan siap menjadi oleh-oleh keluarga di rumah.
Matahari sore kian tenggelam di ufuk barat. Penjelajahan akan berlanjut ke kota lain di sebelah barat Pekalongan.
-bersambung-
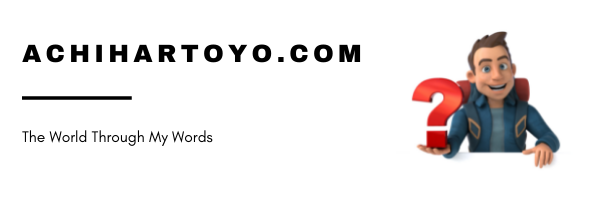





4 comments
Kenapa pas baca announcement mbak2 kereta api auto pke intonasi yak. Hhh
Pekalongan memang surganya batikkk
hehehe
hahaha iya aku bacanya juga pakai suara ala mbak2 itu
wkwkwk